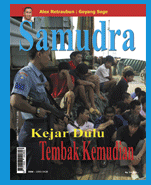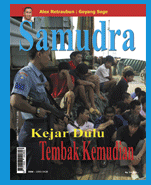Oleh : Soen'an Hadi Poernomo Oleh : Soen'an Hadi PoernomoPenulis adalah Dewan Pakar ASBUMI (Asosiasi Budidaya Mutiara)
Mutiara adalah jenis perhiasan yang termuat di Kitab Suci. Ia menghiasi para ratu dan wanita sejak dulu kala. Produk berharga ini memberi peluang ekonomi sangat tinggi. Sebab, negeri kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan belasan ribu pulau dan berpuluh ribu kilometer panjang pantai.
Namun harapan tersebut akan terwujud apabila disertai pengelolaan yang positif. Kini, mutiara di Indonesia harus dibenahi dari berbagai permasalahan, baik eksternal maupun internal. Padahal, mutiara putih Indonesia adalah termasuk jenis mutiara yang termahal di dunia, yakni South Sea Pearl.
Budidaya mutiara di negeri ini berawal pada tahun 1928 di Pulau Buton, Sulawesi, oleh Mitsubishi Co. Ltd yang bergabung dengan Nanyo Shinju KK. Lantaran pecah Perang Dunia II, usaha tersebut berhenti tahun 1941. Barulah pada 1967 investor Jepang masuk kembali bermitra dengan pengusaha nasional, mendirikan Maluku Pearl-Development. Dalam perjalanan selanjutnya, tumbuh puluhan perusahaan, tentu mengalami pasang-surut, karena problem eksternal dan internal.
Mutiara Putih Indonesia
Mutiara putih Indonesia atau South Sea Pearl, sejenis dengan yang diproduksi oleh Australia, Filipina & Myanmar. Dari volume produksi 9.985 kg, Indonesia adalah yang tertinggi (45 %). Angka itu disusul Australia (32 %), Filipina (17 %), dan Myanmar (5 %). Namun harganya berada pada peringkat ketiga (US$ 16,2 per gram), setelah Australia (US$ 38,4 per gram) dan Myanmar (US$ 25,5 per gram). Ini berarti secara kuantitatif Indonesia berhasil memproduksi mutiara dalam jumlah banyak, namun berkualitas rendah.
Tujuan ekspor utama Indonesia adalah ke Jepang (48,17 %) dan Australia (35,52 %). Adapun provinsi yang mengekspor adalah Bali (34,3 %), Papua (19,73 %), Sulawesi Tenggara (17,06 %), dan DKI Jakarta (15,09 %). Namun produksinya tentu berawal juga dari wilayah lain seperti NTB, NTT, Maluku, dan Lampung oleh 10 perusahaan PMA, 22 swasta nasional, serta 6 PMDN.
Semula mutiara hanya diperoleh dari alam, dalam kerang yang tergolek di dasar laut. Di Jepang, Kokichi Mikimoto melakukan penelitian budidaya mutiara, yang akhirnya berhasil pada tahun 1893. Saat ini budidaya mutiara air tawar juga diproduksi. Namun keelokan mutiara budidaya di laut tetap tak tertandingi.
Mutiara laut ada tiga macam. Pertama, akoya pearl berasal dari Jepang dan Cina. Kedua, black pearl (mutiara hitam) yang diproduksi Tahiti atau French Polynesia. Ketiga, south sea pearl (mutiara putih) produksi Indonesia, Australia, Filipina, dan Myanmar.
Dari ketiga jenis tersebut, yang terbanyak produksinya adalah jenis akoya pearl. Pada tahun 2005, produksi akoya, black, dan south sea pearl berturut-turut adalah 34 ton, 10 ton, dan 8,5 ton. Namun mutiara termahal adalah mutiara putih, yakni rata-rata US$ 23,6 per gram. Sedangkan harga mutiara hitam US$ 14,70 per gram. Malah jenis akoya hanya US$ 3,76 per gram.
Berdasarkan nilai perdagangan dunia, ada tiga negara yang mendominasi produksi mutiara, yakni Jepang (32,22 %), Australia (25,13 %), dan Tahiti (14,41 %). Negara lain berada jauh di bawahnya. Indonesia sendiri masuk peringkat ke-11, yakni hanya 1,41 %.
Problem dan solusi
Masalah eksternal perdagangan mutiara secara umum adalah membanjirnya produk dari Cina. Bagi jenis mutiara putih, kedatangan Vietnam dalam pasar juga turut mempengaruhi, walaupun saat ini produksinya masih 750 kg/tahun.
Tampaknya perlu forum mutiara regional penghasil South Sea Pearl, yakni Australia, Indonesia, Myanmar, Filipina dan Vietnam. Tujuannya, mengendalikan produksi dan meningkatkan kualitas agar harganya dapat terus menguntungkan.
Permasalahan budidaya mutiara di dalam negeri juga cukup kompleks, yakni mengenai kepastian tata ruang, keamanan, pajak dan pungutan, kualitas, serta pengendalian produksi. Usaha budidaya mutiara memerlukan modal investasi yang tidak kecil dan tiga tahun kemudian barulah meraih panen.
Usaha ini keberlanjutannya juga sangat tergantung pada kualitas air yang prima, jernih tapi kaya zat hara, serta memiliki arus yang optimal. Dengan demikian faktor kepastian tata ruang menjadi sangat penting.
Selama ini banyak usaha mutiara terusir karena mendadak muncul kegiatan baru yang sangat mengganggu kehidupan mutiara. Yang paling sering adalah kegiatan pertambangan minyak, semen, emas, dan nikel. Tidak jarang pula, tiba-tiba muncul tambak udang dan mengganggu mutiara yang sedang dipelihara. Penebangan hutan di kawasan hulu tentu berakibat pada kualitas air menjadi berselimut lumpur.
Masalah keamanan juga sempat menjadi horor bagi budidaya mutiara yang kebanyakan berlokasi terpencil, di pulau nan sepi. Bermula terjadi pada tahun 1997, mengalami puncak pencurian pada tahun 1999. Syukurlah, saat ini tindakan kriminal tersebut menurun.
Kebanyakan mutiara yang digasak adalah mutiara siap panen, setelah dipelihara selama tiga tahun. Total kerugiannya bisa mencapai lebih dari Rp 30 miliar. Beberapa perusahaan memilih untuk hengkang, tidak melanjutkan usaha. Di era otonomi daerah ini, timbulnya berbagai pungutan dan pajak aneh-aneh juga menjadi tambahan permasalahan yang cukup merepotkan, misalnya saja PBB laut atau pajak lampu jalan.
Di kalangan pengusaha mutiara juga perlu jeli dan cermat. Artinya, mereka tidak asal berproduksi, banting harga, mengabaikan kualitas, yang akhirnya merugikan, bahkan membunuh usaha mutiara nasional. Lalu bagaimana solusi dari berbagai persoalan tersebut?
Kita bisa menengok sebuah negara kecil di Pasifik Selatan, yaitu Tahiti. Luas Tahiti yang berukuran satu kabupaten di Indonesia saja bisa turut mendominasi pasar mutiara dunia. Bayangkan, produksinya mencapai sepuluh kali lipat dibandingkan Indonesia.
Di sana keamanan secara serius dijaga. Tata ruangnya juga dijamin. Kualitas benar-benar dicermati. Jadi, kalau mau sukses maka pemerintah secara serius harus mengendalikan kualitas dan jumlah produksi. Dengan demikian mutiara Indonesia dapat berkibar mendominasi pasar global, dengan harga yang cukup tinggi.
Segenap pengusaha mutiara harus berkumpul dalam asosiasi. Dan ini merupakan prasyarat untuk pengendalian South Sea Pearl bersama negara lain, yakni Australia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam.
Bercermin ke Tahiti
Salah satu alternatif pengembangan mutiara di Indonesia adalah dengan memilih provinsi atau kabupaten, agar bisa dikelola secara serius dan khusus. Pengelolaan mutiara seperti di Tahiti dapat dijadikan sebagai referensi.
Tahiti atau French Polynesia memang negara kepulauan, tapi luas wilayahnya cuma 1.045 km2 dengan penduduk 178.133 orang. Itu berarti hanya dua pertiga luas Kabupaten Karimun (1.524 km2) yang berpenduduk 162.829 jiwa.
Soal kehebatan Tahiti membudidayakan mutiara jangan diragukan lagi. Negara itu menghasilkan devisa US$ 160 juta dan membuka kesempatan kerja untuk 7.000 orang. Di sana terdapat 4 pulau dan 26 atol digunakan untuk kegiatan budidaya. Sedangkan 15 atol dipakai untuk pengumpulan anakan kerang (spat collection).
Pada tahun 1960 mulai dicoba budidaya, dan baru berhasil memanen mutiara bulat pada tahun 1968. Pertengahan tahun 1970-an, mutiara hitam dari Tahiti mulai masuk pasar internasional atas promosi Amerika dan Perancis.
Perkembangannya terus menanjak. Dalam kurun waktu 1980 - 1990, produksinya sekitar 20 kg. Lalu naik menjadi 600 kg. Pada tahun 2000 sudah mencapai 11 ton.
Pengusaha mutiara pada tahun 1975 baru ada 3 perusahaan. Namun 10 tahun kemudian mencapai 110 perusahaan. Bahkan tahun 1995 meningkat menjadi 2.399 perusahaan. Pada saat krisis moneter 1998 pun terdapat 2.745 perusahaan.
Namun masa krisis itu menunjukkan fenomena yang menimbulkan curiga. Dari 1998 - 2000 walaupun volumenya naik 240 %, tapi nilainya hanya 23 %. Bahkan pada tahun 2000 - 2003 mengalami stagnasi volume, nilainya anjlok 50 %, dari US$ 160 juta menjadi hanya US$ 80 juta.
Kiat Tahiti menghadapi krisis mutiara juga patut ditiru. Stagnasi tahun 2000, dinilai sebagai kejenuhan dan produksi yang tidak terkendali. Mereka menyebut anarchic mass production of lower quality pearl. Pemerintah membentuk Kementrian Urusan Mutiara yang dipimpin langsung oleh Presiden Gaston Fosse.
Perusahaan-perusahaan ditertibkan. Manajemen audit terhadap teknis dan finansial dilakukan. Kepatuhan terhadap aturan sosial dan perburuhan dievaluasi. Fasilitas pendataan dicek. Terhadap SDM dilakukan uji sertifikasi. Dari 2.745 perusahaan, yang lulus hanya 865, dan akhirnya tinggal 300 perusahaan.
Penertiban ekspor juga dilakukan. Hanya mutiara berkualitas yang diijinkan. Standar mutu ditetapkan, dikontrol melalui uji visual dan ultraviolet. Pajak ekspor dinaikkan agar pengusaha tidak asal mengirim ke luar negeri. Yang tidak layak ekspor ditumbuk untuk didaur ulang menjadi bio-coated nuclei.
Pada Juni 2003 diadakan upacara membuang ke laut 33.000 butir mutiara berkualitas rendah, sebagai peringatan keseriusan untuk berpihak pada mutu. Sejak itu, mutiara hitam dari Tahiti harganya di pasar internasional mulai naik dan bangkit kembali.
Nah, dengan mencermati akar permasalahan, merenung solusi yang memungkinkan, dan bercermin pada keberhasilan bangsa lain, tidaklah berlebihan kalau Indonesia kelak menjadi ratu mutiara dunia. Syaratnya, segenap pihak harus serius. Pengusaha harus bersatu dan memiliki komitmen. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberi dukungan optimal untuk jangka panjang, bukan setoran taktis sesaat.
Kiranya tidak perlu memandang terlalu lebar ke seluruh bentangan Nusantara. Cukuplah memilih beberapa lokasi untuk dikembangkan secara serius. One district, one product, yakni high quality of south sea pearl. Dan kita pun akan sepakat, bahwa small is great, not just beautiful. ***
|